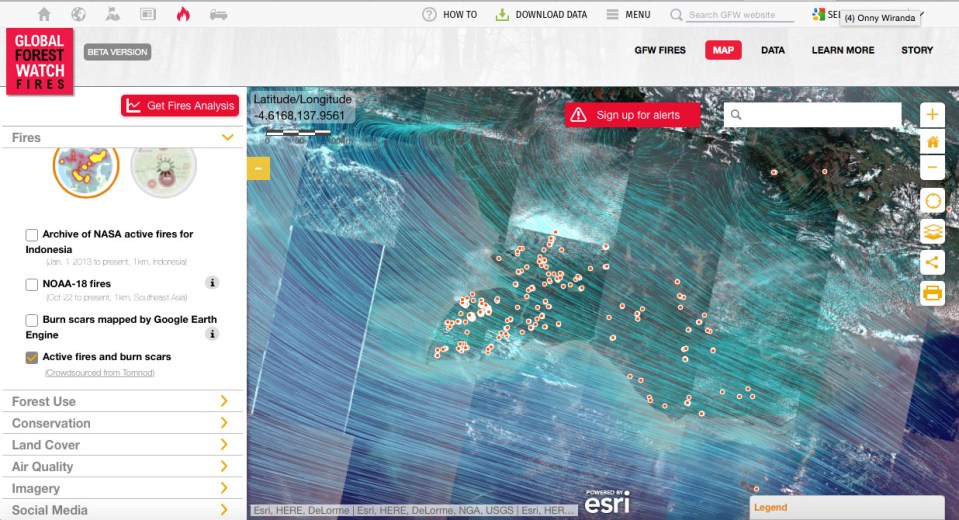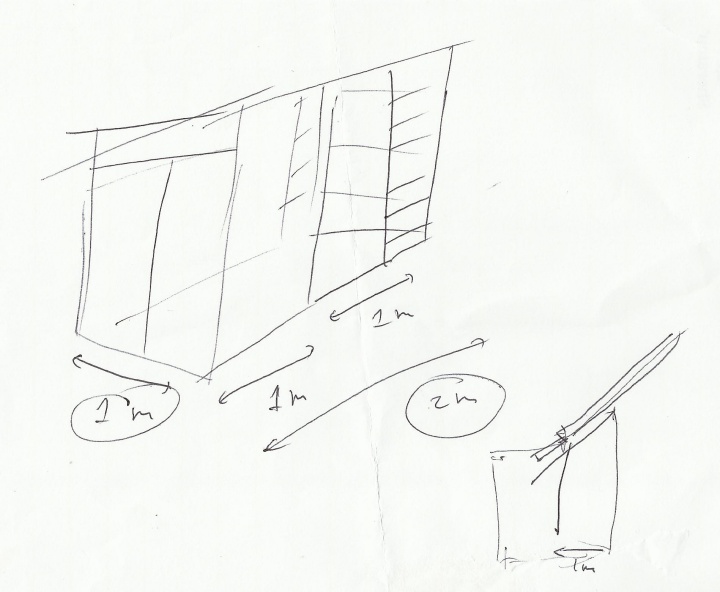Patung Mozes Kilangin di depan Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika (TIM), Papua
Dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, seorang anggota Mahkamah bertanya kepada Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, mengenai penerbangan mereka dengan helikopter ke Urumuka untuk melihat tempat yang akan menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air.
Sekalipun hanya sebuah kampung kecil di sebelah timur Timika, Urumuka memiliki arti strategis karena di situ akan dibangun sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air yang akan memberikan pasokan listrik bagi kota Timika dan bagi Pabrik Pengolah Tembaga yang akan dibangun Freeport di pelabuhan Timika.
Pada tahun 1936, sebuah tim ekspedisi Belanda berhasil mencapai puncak gunung bersalju di pegunungan tengah Papua. Tim itu terdiri dari Anton Hendrijk Colijn, Frits Julius Wissel, dan Jean Jacques Dozy. Mereka terkejut karena mendapati sebuah gunung yang terdiri dari tembaga dan karena itu mereka beri nama Erstberg (Belanda: Gunung Tembaga). Oleh orang Amungme, gunung itu adalah tempat keramat dan dikenal sebagai Nemangkawi Ninggok. Laporan ekspedisi Colijn kemudian lama teronggok di sebuah perpustakaan di Belanda.
Laporan Colijn baru dibaca kembali pada tahun 1960, saat pemerintah Belanda baru berminat mengeksplorasi Erstberg. Pemerintah Belanda melalui NHM bekerjasama dengan sebuah perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport Sulphur Company, untuk kembali melakukan ekspedisi. Tapi memasuki pertengahan tahun 1960, situasi politik berubah dengan cepat. Bung Karno mengintensifkan kampanye perebutan Irian Barat dari tangan Belanda. Situasi politik internasional yang saat itu lebih menguntungkan Indonesia membuat Belanda pasrah pada tekanan Amerika Serikat. Pada 5 April 1967, Freeport Sulphur Company tidak lagi berurusan dengan Pemerintah Belanda. Mereka sudah membuat Kontrak Karya selama 30 tahun dengan Pemerintahan baru Indonesia di bawah Mayjend Soeharto, yang secara tergesa-gesa membuat Undang-Undang baru untuk menaungi kontrak istimewa ini. Rencana itu ternyata tidak semudah di atas kertas. Orang Amungme menolak keras rencana pengeboran gunung keramat mereka.
Dari Gunung ke Pantai
Mozes Kilangin dilahirkan di Diloa, sebuah kampung orang Amungme di pegunungan tengah Papua, pada tahun 1925 dari pasangan mama Awesomki Wanmang dan bapa Kilangin Tenbak. Mozes kecil tumbuh sebagai anak tunggal karena dua saudaranya meninggal dunia saat masih kecil. Suatu hari pada pertengahan tahun 1940, Mozes ikut bepergian dengan orang tua dan warga kampung untuk melakukan barter dengan orang Kamoro yang tinggal di daerah pesisir. Di tengah perjalanan melalui medan berat antara gunung dan daerah dataran rendah, Mozes terpisah dari rombongan dan tersesat. Mozes kemudian tinggal bersama keluarga guru asal Maluku di Koperapoka, sebuah kampung di pesisir Mimika. Di situ, dia mulai dikenal dengan nama barunya, Mozes Kilangin.
Mozes kemudian dikirimkan untuk sekolah di Kaokanao, pusat misi Katolik dan pemerintahan Belanda untuk wilayah selatan Papua. Mozes lulus VV (Ver Volgschool) di Merauke pada tahun 1950. Setelah itu Mozes melanjutkan pendidikan di OVVO (Opleiding Voor Volks Onderwijzer/Sekolah Guru) di Fak-fak dan lulus pada tahun 1953. Setelah lulus, Mozes dipercaya Pater Kammerer di Kaokanao pergi ke daerah pegunungan, untuk mencari anak Amungme yang mau mendapatkan pendidikan sebagaimana halnya Mozes.
Mozes Kilangin sangat bersemangat melihat anak-anak Amungme mendapatkan pendidikan. Pada bulan Desember 1953, Mozes membawa lima anak Amungme dari Tsinga untuk belajar di Kaokanao.
Belum lama ini saya sempat berjumpa dengan Bapa Karel Beanal, salah satu dari lima anak Amungme pertama yang dibawa Mozes Kilangin untuk mendapatkan pendidikan dari Belanda. Sekalipun sekarang sudah berusia 75 tahun, Pak Karel masih nampak sehat dan ingat semua pengalaman semasa di asrama dan saat menempuh pendidikan di OVVO (bahkan masih bisa berdoa Bapa Kami dalam bahasa Belanda). Sampai akhir masa pensiunnya, Pak Karel adalah seorang guru yang berpengetahuan dan berdedikasi. Saya jadi membayangkan kenapa pendidikan Indonesia tidak bisa menghasilkan orang Papua sekelas Mozes Kilangin dan Karel Beanal.
Setelah bekerja sebagai guru selama hampir setahun di daerah pegunungan tengah daerah orang Mee, Mozes Kilangin mengajukan surat kepada Pater Kamerer. Mozes ingin bekerja di kampung halamannya sendiri, mendidik orang Amungme. Pater Kamerer mengabulkan permohonan ini. Mozes kemudian mejadi guru agama di Amyakagama, kampung orang Amungme di daerah dataran tinggi. Selain menjadi guru, Mozes juga aktif dalam kehidupan bermasyarakat orang Amungme. Mozes mengorganisir pembangunan rumah guru, pastoran, menjadi juru damai antara marga-marga suku Amungme yang saling berperang, dan menyakinkan orang Amungme untuk mau pindah ke daerah dataran rendah. Karena di dataran rendah, pelayanan masyarakat yang dilakukan gereja Katolik akan lebih mudah dibanding jika dilakukan di daerah dataran tinggi Papua. Atas ketekunan dan pengabdiannya kepada orang Amungme, Mozes Kilangin kemudian dipercaya menjadi Kepala Distrik Akimuga, sebuah daerah di dataran rendah yang menjadi tempat tinggal baru orang Amungme. Mozes Kilangin mulai dikenal orang Amungme sebagai seorang Uru Me Ki (Bahasa Amungme: Guru Besar).
Kita Cubit Dulu
Setelah ditandatanganinya Kontrak Karya pada tahun 1967, Freeport langsung bergegas membuka hutan di sekitar Gunung Erstberg dan mengirimkan berbagai macam peralatan untuk kegiatan pengeboran. Semua dilakukan tanpa melibatkan orang Amungme sebagai pemilik hak ulayat daerah tersebut. Orang Amungme, khususnya yang timbal di daerah Waa dan Banti, merasa tersinggung dengan tindakan sepihak tersebut dan kemudian menutup wilayah di sekitar Nemangkawi dengan patok-patok.
Pihak Freeport kemudian menugaskan dua orang stafnya untuk menjemput Mozes Kilangin di Akimuga. Dengan harapan supaya Mozes dapat membantu memberikan penjelasan kepada orang Amungme yang marah. Awalnya Mozes merasa enggan membantu. Tapi setelah dibujuk dengan susah payah, Mozes akhirnya bersedia.
Sebuah helikopter Freeport kemudian membawa Mozes terbang dari Akimuga ke lokasi pengeboran. Di sana, Mozes mendapati orang-orang Amungme yang rupanya semakin marah karena kehadiran polisi. Mozes menjelaskan bahwa proses pengeboran yang dilakukan oleh Freeport ibaratnya seperti “kita orang Amungme beli tembakau isap itu. Sebelum kita beli, kita cubit dulu atau ambil sedikit untuk rasa dulu. Kalau baik baru kita beli.” Selanjutnya Mozes juga menjelaskan manfaat jika “hasilnya bagus”, maka “suatu saat nanti kamu punya masa depan dan anak-anak akan lebih baik. Barang-barang yang belum kamu punya dan belum lihat dunia di luar sana, nanti kalian akan lihat juga.”
Mendengarkan penjelasan itu, orang Amungme mengalah dan mengizinkan kegiatan pengeboran berjalan kembali. Sebagai ungkapan atas besarnya jasa Mozes Kilangin bagi Freeport, bandara di Timika yang dibuka Freeport pada tahun 1970 diberi nama Bandar Udara Mozes Kilangin. Kini bahkan dihiasi dengan patung Mozes Kilangin yang sedang mengenakan jas seperti sedang menghadiri rapat direksi Freeport.
Dalam buku biografinya, Mozes Kilangin mengingatkan bahwa “kalau ada hasil, bicara baik-baik dengan masyarakat. Jangan meremehkan masyarakat. Perhatikan mereka punya pendidikan, kesehatan, perumahan yang baik. Hak-hak masyarakat harus dihargai, dan hormati masyarakat Amungme sebagai penduduk asli dan sebagai manusia.”
Sekalipun cukup besar jasanya bagi Freeport, Mozes memilih tetap melanjutkan profesinya sebagai seorang guru di Kaimana dan kemudian diserahi tanggung jawab oleh pemerintah untuk membuka daerah baru di Timika sebagai tempat tinggal orang Amungme. Paitua yang pernah mendapat penghargaan dari Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II atas dukungannya pada Misi Gereja Katolik di Papua ini meninggal dunia dengan damai di Timika pada 18 Agustus 1999.
Hingga sekarang, pesan Mozes Kilangin masih terasa sangat kontekstual. Terlebih di saat segelintir orang di Jakarta yang dengan serakahnya ingin meraup keuntungan dan sama sekali tidak menghargai orang Amungme, sebagaimana pesan paitua Mozes dalam buku biografinya.