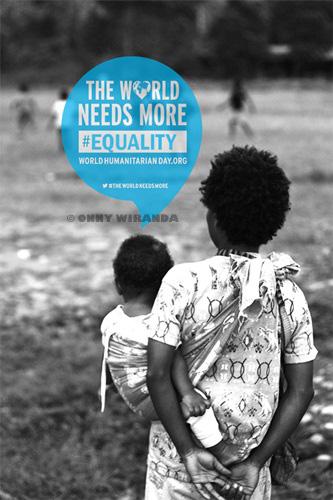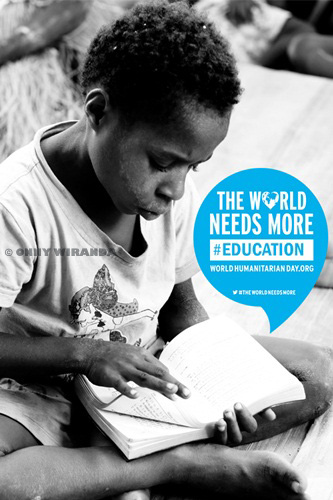Eri Susanto (paling kanan berkemeja batik) di sebuah acara. Foto: Romo Didik.
Aku lupa pastinya, kapan dan bagaimana aku mengenal seorang Eri Susanto. Yang aku ingat hanya latar belakangnya, yakni suasana antara bulan April 1997 hingga Mei 1998; kekesalan akan “kuningisasi”, Pemilu palsu dan pidato2 yg menjemukan, paksaan halus tapi mengancam untuk pilih Golkar, kecongkakan tentara yang -pada suatu hari di tahun 1997 saat aku masih SMA- menggebuki dengan tanpa ampun beberapa pemuda yang sepertinya baru saja demo di dekat sekolahku.
Pada bulan Februari 1998, di Universitas Kristen Petra saat itu, suasana yang aku rasakan itu tidak terasa di kampus. Hidup berjalan sebagaimana adanya. Tapi ternyata ada juga beberapa orang yang sama sumpeknya dengan aku. Ada Doyok, Dimas, Edo, Casper, Joseph, Eri, Duro, Herwindo, Sondik, Gunawan, Christo, Yudi, Hok Gwan, Dwi, Linus Ireeuw, dan banyak teman lain. Sebuah nama kemudian dipilih; GEMPUR. Singkatan dari Gerakan Mahasiswa Petra untuk Reformasi. Seingatku ada yang sempat permisi dengan Gempur Aji Pambrasto, mahasiswa Arsitek 1995 yang namanya cerminan semangat anti-Soeharto dari ayahnya. Awalnya Gempur Soeharto tapi terus diganti jadi Gempur Adi Pambrasto (Pasukan Pemberantas Soeharto). Hehe.
Semua mahasiswa yang terlibat di GEMPUR memiliki selera dan ketajaman masing-masing dalam diskusi politik. Yang paling asyik aku amati adalah Doyok, Eri, dan Dimas. Mungkin karena mereka lebih senior dan banyak pengalaman. Tapi diskusi dengan Eri lebih dari sekedar rame membahas kebusukan rezim Orba dan teori2 konspirasi yang laris sekali saat itu atau rencana demonstrasi. Dari sekedar kesal dengan rezim Orba, aku “dikenalkan” dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati, tentang hubungan antara teologi dengan perubahan sosial, tanpa banyak mengumbar jargon, apalagi menyuruh membaca “Dasar-dasar Ilmu Politik” karangan Miriam Budiarjo.
Padahal saat itu yang diutamakan adalah yang berani turun ke jalan dan meneriakkan jargon2 perubahan. Sesuatu yang hanya selang setahun sebelumnya dipandang sebagai tindakan makar. Mahasiswa Petra yang sebelumnya dipandang tidak akan berani turun ke jalan ternyata ikut turun juga. Sekalipun awalnya, aku ingat sekali, sempat di-briefing dulu supaya menjaga diri.
***
Pada 21 Mei 1998, secara mengejutkan sang jenderal memilih untuk “lengser” (sumpah aku benci sekali istilah ini). Suasana mendadak berubah; dari suasana ketakutan setelah peristiwa kerusuhan rasial di beberapa kota besar Indonesia dan semangat perubahan total menjadi kegembiraan yang hampa dan singkat. Setelah itu banyak orang bilang supaya kembali hidup normal karena soeharto sudah pergi. Seolah-olah dengan soeharto pergi, Indonesia sudah sembuh dari pileknya. Padahal ini bukan pilek, ini sinus, pikirku saat itu. Perlu perawatan, perlu pengetahuan akan penyakit itu, perlu menaksir seberapa banyak kerugian yg dialami, perlu tahu bagaimana agar tidak kena sinus lagi. Mundurnya soeharto telah menjadi sebuah “placebo” yang manjur.
Kita semua galau (sekalipun saat itu istilah galau beda penggunaannya). Soeharto memang sudah turun, tapi masa gitu aja sih? Apakah masalahnya hanya di soeharto? Bagaimana dengan pemerintahan yang dia bentuk sekarang ini, bagaimana dengan hartanya yang diambil dari kekayaan alam bangsa ini?
GEMPUR masih sering mendiskusikan perkembangan politik dan memikirkan langkah berikutnya. Kami masih turun ke jalan dan berjejaring dengan mahasiswa dari kampus lain di Surabaya. Sekalipun soeharto sudah mundur, tapi masih ada Dwifungsi Abri, Pemilu yang dijanjikan haruslah Pemilu multipartai, dan soeharto harus diadili atas semua kejahatannya. Seperti daftar belanjaan, kami terus berusah mencentang semua daftar belanjaan yang sudah didapatkan.
Kalau tidak salah pada bulan Agustus 1998, aku ikut Workshop Analisa Sosial di Paroki Aloysius Gonzaga, Surabaya sesuai “ajakan” Eri (ah, entah itu Eri yang ajak atau aku yang merasa terajak akibat sering ngobrol dengan Eri). Workshop itu dipimpin seorang imam Jesuit, namanya Romo Suryawasita, Sj. Gayanya mirip Eri, nyantai tapi penuh pengetahuan.
Rasanya seperti memilih pil warna merah di film Matrix. Pil yang membuatmu tersentak dari kenyamanan dan merasakan pahitnya realita; tidak sekedar melihat keadaan dan fenomena, tapi mendalami fakta. Melihat sejarah bukan sekedar rangkaian kejadian, tapi sebuah dialektika. Tidak hanya menggunjingkan gagasan tapi menuliskannya. Tidak lagi hidup di dunia yang semu nan kaku, tapi mulai mendekati kesejatian.
Tidak hanya perkara soeharto mundur tapi soal ketidakadilan sosial yang telah membelenggu negeri ini sejak 1965. Tidak hanya soal korupsi dan nepotisme Keluarga Cendana, tapi soal akumulasi modal di tangan segelintir orang. Tidak hanya soal sekumpulan anak muda yang marah, tapi soal kelas menengah yang kuat dan mau berkorban.
Eri juga mengenalkan aku ke lingkungan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ke sebuah kampung di Surabaya. Saat itu aku terkaget-kaget melihat alm. Brewok yang memang brewok betul dan teman2nya yg jam 11 malam masih ngopi dan ngobrol soal politik, ketemu seorang pengurus PRD Surabaya yang namanya ajaib bagiku; Safii Kemamang, soal terawangan Brewok tentang Bimo Petrus yang diduga berada di sebuah tempat di Jakarta.
Yah, seperti di film Matrix, kamu tiba2 menemukan dirimu di antara orang2 yang oleh dunia yang mapan dipandang sebagai manusia yang aneh, yang dengan bodohnya menempatkan dirinya di luar sistem. Padahal kalau kamu manut dengan sistem itu, hidupmu niscaya akan “baik2 saja”.
***
Akibatnya cukup jelas. Drama pengunduran diri soeharto, yang telah menjadi “placebo” sakitnya demokrasi Indonesia saat itu tidak mempan untukku. Sekarang masalahnya bukan hanya menyeret soeharto ke pengadilan, tapi bagaimana mengubah sistem demokrasi dan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat.
Seiring dengan itu, aku semakin jarang bertemu Eri. Aku lebih sering bertemu orang2 yang dikenalkan oleh Eri kepadaku, membaca buku-buku yang topik dan temanya aku kenal dari Workshop Ansos bersama Romo Suryo. Kalau tidak salah, menjelang akhir masa pemerintahan Gus Dur, Eri juga punya tugas lain untuk diselesaikan; studinya. Demikian pula dengan diriku. Bisa kuliah di Petra itu hasil keringat orang tuaku, karena itu harus aku selesaikan, seberapapun jengahnya. Dengan berat hati, dunia aktivisme politik aku tinggalkan.
Kontak semakin terputus setelah aku lulus, apalagi sejak aku pindah ke Papua tahun 2008. Padahal setiap bernostalgia soal 98, aku selalu menyebut Eri sebagai salah satu orang yang punya pengaruh besar, seorang “influencer” atau “maven”, tapi tidak pernah mencoba meluangkan waktu menjalin kembali pertemanan. Rasanya seperti punya hutang.
Hutang yang sekarang aku rasakan datang menagih dengan lembut sekaligus mau meminta pemutihan karena sudah seharusnya lunas, saat aku mendengar berita kepergian Eri di Facebook. Sekalipun diputihkan, ada syarat yang harus aku jalani, mengucapkan terima kasih dan menggambarkan seorang Eri yang aku kenal. Ga perlu terlalu banyak kata: Kamu orang hebat, Eri. Aku menghormatimu.
Kepergianmu pun menjelang peringatan St. Ignatius Loyola yang jatuh setiap tanggal 31 Juli, pembaharu gereja dan peletak dasar Ajaran Sosial Gereja. Seolah kamu menegaskan bahwa hidup ini adalah soal memilih, hidup biasa-biasa saja atau hidup luar biasa, menjadi sekedar teman cangkruk atau menjadi teman dalam perutusan, seperti di film Matrix –memilih melihat yang semu atau yang sejati- dan seperti yang diajarkan St. Ignatius Loyola, untuk “memilih apa yang lebih membawa aku kepada semakin besarnya kemuliaan Allah dan keselamatan sesama.”
Selamat jalan, Eri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah membantu aku memilih menjalani hidup yang tidak biasa-biasa saja tapi juga tidak berusaha nampak sebagai orang yang luar biasa.