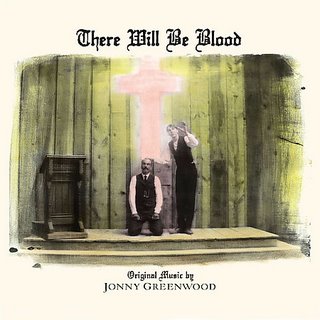halo gundul, sori ya kemarin aku tinggal sendirian. selamat paskah.
Definisi
Definisi memang selalu bikin repot. Gara-gara definisi ”beragama” dan ”tidak beragama”, sebuah obrolan ringan tentang kehidupan masyarakat Samin jadi serupa debat antara Santo Paulus dan para filsuf Yunani tentang ”kabar gembira” di Akropolis. Orang-orang yang merasa “beragama” mempermasalahkan “ketidakberagamaan” orang Samin dengan kepercayaan Adam mereka. Gara-gara definisi “ga dalem” kaki saya melangkah tenang melintasi genangan air (yang ternyata cukup dalam) dan akhirnya gatal-gatal kena kutu air.
Dari para hadirin yang menyerang orang Samin dengan dakwaan ”tidak beragama”, saya bisa memahami mengapa Neil Britton mengatakan bahwa selain alat bantu berpikir, definisi juga soal “orientasi mental dan emosi, model pemaknaan, dan cara pandang pemberi definisi”. Definisi Neil Britton soal definisi ini saya baca di sebuah tulisan soal Lapindo di Kompas, Kamis, 28 Februari 2008.
Kasus Lapindo menyertakan banyak orang biasa membuat definisi, mulai dari para pebisnis, ilmuwan, kalangan media, politisi, pelagak, pakar hukum, dan anggota parlemen yang terhormat. Banyak banget, ya. Mungkin ini salah satu kolaborasi interdisipliner paling luas yang pernah terjadi di republik kita setelah Orde Baru dengan proyek bahasa mereka.
Bedanya proyek yang ini diprakarsai oleh para pebisnis di grup usaha yang kepalanya sekarang menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Para pebisnis ini mempekerjakan para ilmuwan untuk menyediakan berbagai pembenaran ilmiah bahwa yang terjadi di Sidoarjo adalah ulah alam yang “mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis” (UU No. 24/2007). Dengan kekuatan media dan modal, dengan mudah pula mereka mengumumkan usaha dan bantuan Lapindo bagi para korban yang ditulis oleh para public relation dan copywriter yang paling handal (semoga jiwa kalian diampuni). Dan dengan tenang, Bapak Aburizal Bakrie bisa menjalankan tugas mulia sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sementara grup bisnisnya dengan mulus melakukan perluasan bisnis, menyuruh Karni Ilyas mengurus stasiun televisi barunya, dan memulai proyek properti. Indahnya dunia ini…seindah jargon perusahaan-perusahaan besar dan jargon salah satu perusahaan milik Pak Menteri…Dream. Drowned. Death.
Kata-kata indah itu tidak akan pernah dipahami oleh para korban Lapindo, baik yang jauh-jauh pergi ke Jakarta dan yang mati-matian mempertahankan kehidupan mereka di pengungsian di Pasar Porong. Mereka tahu bahwa negara dan rakyat berada di posisi yang berseberangan. Negara dengan nyaman duduk bersama para pebisnis. Mereka tahu bahwa ada negara lain yang menguasai negeri ini, namanya korporasi.
Sementara itu, wakil presiden kita dengan lantang bilang bahwa republik ini harus diurus oleh seorang pebisnis. Dengan pengandaian bahwa “negara” adalah “perusahaan” yang harus mengusahakan keuntungan dan …yah sekedarnya menyediakan sebagian keuntungan untuk para karyawan yang loyal dan rajin…biar mereka ga minta macam-macam atau keburu pindah kerja…dan membuat laporan tahunan yang sophisticated untuk para pemegang saham dan investor yang terhormat…
Maka jadilah Kasus Lapindo sebagai salah bukti sesat logika yang sekarang sedang berlangsung. Hukum dan ilmu pengetahuan dimiliki oleh para pemilik modal serta digunakan untuk mengamankan modal dan mengeruk keuntungan. Para ilmuwan geologis sedunia yang kumpul di Jakarta beberapa waktu lalu bilang kalau Lumpur Lapindo adalah bencana alam. UU No. 24/2007 menyebutkan bahwa “bencana alam” dan “bencana non-alam” memilik arti dan konsekuensi yang jelas. Maaf, ya, di UU tidak ada pasal yang menjelaskan peristiwa yang saling terkait, kecerobohan yang memicu kejadian alam yang ekstrem misalnya. Misalnya eksploitasi hutan yang menyebabkan banjir bandang. Eksplorasi ya eksplorasi. Lumpur ya Lumpur. Cobaan Tuhan. Kalau masih penasaran coba aja cari di UU sejenis yang ada di Finlandia atau Peru. Mungkin ada. Hihihi…
Do you care?
Mitos
Ternyata aku tidak sendirian. Seseorang di kantor sekarang sedang resah, sekalipun dengan sumber keresahan yang agak berbeda.
Dia merasa bahwa profesinya (yang sudah digelutinya selama lebih dari 5 tahun –rentang karir yang tidak pernah bisa aku bayangkan) adalah produsen mitos, yang membuat orang terus menerus mengkonsumsi. Dalam beberapa obrolan, dia selalu menekankan betapa hebatnya kapitalisme bisa menghegemoni masyarakat Indonesia, membuat orang Indonesia dengan suka rela nonton film-film Hollywood, memimpikan berbagai macam merek hape, seperti menggiring orang untuk bunuh diri minum racun tikus rasa strawberry atau chocolatino. Tersedia banyak pilihan rasa!
Tidak heran, setelah dia ngeloyor pergi sambil menggaruk-garuk kepalanya, seorang teman lain menyeletuk: ”Walah, baru sekarang sadar kapitalisme itu ganas? Nang ndi ae, Mas?”
”Yaa, habis gimana ya, perkembangan kapitalisme sekarang ini sampai bisa menciptakan berbagai macam mitos.” timpalku sambil melahap lumpia murahan yang aku beli di depan kantor.
”Mitos?”
”Begitu banyak hal yang kita terima begitu saja, teken for grentet…”
”Misalnya?”
”Iklan cuma salah satunya, nah gosip artis misalnya, kita kan menganggap bahwa gosip adalah informasi yang harus kita lahap juga.”
”Terus mau diapain?”
”Jangan asal terima saja, semua yang kita konsumsi harus kita sikapi dengan kritis.”
”Rokokmu itu rokok Amerika, kenapa ga ngerokok kretek asli Indonesia?”
”Nah itu lain, Bung. Itu masalah selera…”
“Lha mbok berpikir secara kritis soal seleramu itu.”
”Begini…”
Kisah selanjutnya akan percuma saja aku ceritakan di sini. Yang jelas pagi itu aku kembali ke meja kerja dengan sebuah kesimpulan: manusia semacam temanku (dan aku sendiri juga mungkin) yang telat itu jumlahnya banyak sekali. Sesuatu membuat mereka sadar bahwa ada proses pengerdilan diri dan penenggelaman kemanusiaan yang sedang berlangsung, tapi tidak merasa tidak bisa (baca: tidak mau) berbuat apa-apa. Iklan-iklan televisi mungkin jadi semacam pisau bermata ganda, selain melenakan dia juga perlahan menumbuhkan sikap kritis, sekalipun samar-samar.
Setiap hari mereka terbangun dikelilingi mitos, mulai dari rokok yang mereka beli karena iklan yang lucu, teh celup atau kopi instan, gosip artis, guyonan politik, berita kriminal. Hingga mungkin 60% mimpi mereka adalah hasil penerimaan mereka atas berbagai mitos yang menyergap diri mereka setiap hari dan diterima begitu saja seperti halnya udara.
Tidak heran juga jika Octavio Paz menyerukan ajakan yang sama sangarnya dengan simpulan Karl Marx: manusia modern mampu merasionalisasi mitos, tapi tidak mampu menghancurkannya.
Salam Damai,
Selamat nonton Jerry Maguire….
PS: Lha terus apa keresahanku? Sederhana saja, Bung: bosan jadi orang kantoran…hehe…dan ngeri aja membayangkan setelah bekerja sekian lama baru sadar, seperti temanku yang sekarang terlihat semakin melankolis saja setiap hari.
Pulang
Nana,
Tahukah kamu kapan sebenarnya kita layak menulis dengan kalimat pembuka semacam “sepuluh tahun yang lalu…” atau “sepuluh musim hujan yang lalu…”
Tadi pagi sebelum kita berangkat aku terbangun dengan perasaan bahwa sekarang ini saya sudah sangat layak menulis dengan kalimat pembuka semacam itu. Sama layaknya dengan Jean Valjean di Les Miserables yang berjumpa dengan inspektur polisi yang terus memburunya hanya karena Jean Valjean, ketika dihimpit rasa lapar, mencuri roti.
Aku terbangun di ranjang yang sama di kamar yang sama, membuka jendela besar yang sama, dan menatap langit yang sama, di sebuah waktu yang dulu sama sekali tak terbayangkan akan aku lewatkan di tempat yang persis yang sama. Dulu aku mengira bahwa aku akan hidup di tempat yang jauh dari rumahku, di antara keluarga baru, teman-teman baru. Yang membedakan hanyalah jajaran pohon pisang yang menggantikan pohon angsana dan hujan yang turun demikian derasnya.
Dulu aku mengira bahwa kalimat pembuka atau suasana jauh di masa depan akan membuat tulisan dan imajinasi akan semakin terbang luas dan membuatmu kagum. Ternyata tidak. Kamu justru malah tidak bisa menangkap suasana “megah” yang aku sodorkan. Ya, kan? Aku sendiri merasa bahwa tulisan semacam itu sebenarnya tindakan nekat yang mengerikan. Mengingkari kekinian dan masa kini adalah kebodohan terbesar yang pernah aku lakukan. Jauh sebelum tadi pagi aku sudah bersumpah untuk tidak akan menempatkan tokohku atau aku sendiri di masa depan yang masih jauh sekali menjelang.
Selama dua tahun aku sebenarnya sempat merasakan “masa depan” dan semua suasana yang tadi aku jelaskan, di sebuah kota yang bersahaja dan tidak dihablur kemewahan seperti kota ini.
Mendadak kini aku menjumpai diri berada di tempat yang sama, seolah dua tahun di tempat baru dan keluarga baru yang terdiri dari teman-temanku itu hanya terjadi di mimpi seseorang dan kebetulan aku menghadiri kemeriahan mimpi itu. Aku cuma tersenyum pahit menyadari keadaan ini. Kenapa dulu aku memilih pulang ke rumah ini dan meninggalkan rumah baruku? Kamu ingat kan dulu aku pernah bilang bahwa aku selalu siap menanggung semua keputusan yang aku bikin, yang baik dan buruk, yang tepat dan luput. Kini aku sedang menanggungnya, Nana.
Mungkin kita tidak akan pernah berhak menulis tentang diri kita di masa depan, kecuali kita pernah hidup dua kali atau kita masih ingat pengalaman hidup kita di kehidupan yang lampau.
Sepuluh tahun sungguh tak terasa. Semua novel dan roman itu benar soal kegentaran manusia menghadapi waktu dan diri manusia sendiri. Seseorang bisa memilih apakah akan berkembang atau tetap kerdil selama sepuluh tahun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menilai baik buruknya perkembangan seorang manusia, kecuali jika manusia itu ditempatkan di bawah ukuran tertentu seperti yang berhak dilakukan guru, akuntan, atau pengamat sosial. Apakah manusia Indonesia selama sepuluh tahun ini mengalami perkembangan, kita bisa menilainya dengan mudah dari ukuran seperti Human Development Index misalnya. Tapi untuk mencatat perkembangan manusia hanya penulis yang bisa menuliskan, dan alih-alih memberikan jawaban jelas para penulis itu pasti malah akan mengajukan pertanyaan.
Satu simpulan sudah aku dapatkan, Nana. Soal apa? Soal apalagi kalau bukan perjalanan menembus waktu yang begitu rapuh ini, soal perjalanan yang entah perjalanan berangkat atau pulang ini. Mau terlihat bermakna atau sia-sia hanya soal kapan kita memikirkan hal itu. Rasanya aku sungguh beruntung memikirkan hal itu di sebuah hari libur yang basah dan di sebuah tempat pertama kali aku memikirkan ngerinya perjalanan manusia. Semoga kamu juga mendapatkan keberuntungan semacam itu.
Cium dan peluk untukmu
There Will Be Blood OST
Soeharto dan Orde ”Tak Tersentuh”
Oleh Andi Arief
Soeharto adalah diktator yang berhasil. Apa boleh buat, dari satu iklim politik yang suka latah seperti sekarang, saya terpaksa mencatatnya begitu. Kepergiannya kemarin diiringi liputan media massa luar biasa, live, on the spot, real time, menit per menit. Kentara sekali jika obituarinya telah selesai ditulis, atau direkam, jauh hari sebelum bekas penguasa rezim Orde Baru itu meninggal dunia.
Media massa, meski tak semua, menghadirkan liputan kematiannya bak sebait ode bagi seorang yang sarat tanda jasa. Satu stasiun televisi bahkan memutar kembali riwayat hidupnya dengan iringan lagu “Gugur Bunga”. Terkesan kepada kita Soeharto seperti seorang pahlawan besar yang tamat berlaga di medan perang. Tapi bagi saya, lagu itu justru menyeret ke arah komplikasi sejarah, dan juga hari depan politik Indonesia. Satu momen yang tiba-tiba membuat saya terlempar ke masa sepuluh tahun silam.
Dari sudut sel gelap tempat saya ditahan aparat keamanan Orde Baru, sayup-sayup terdengar lagu “Gugur Bunga” menyayat. Hari-hari di Bulan Mei 1998, dari radio transistor penjaga sel, telinga saya menangkap berita tiga mahasiswa ditembak mati di Universitas Trisakti. Mereka jadi martir gerakan mahasiswa pro demokrasi dan rakyat yang tak percaya lagi dengan rezim Orde Baru. Saya dan kawan-kawan mahasiswa yang diculik, lalu ditahan itu yakin, inilah orkes pembuka bagi tumbangnya kediktatoran.
Sepekan kemudian, Soeharto mundur. Lakon Indonesia yang hamil tua itu akhirnya usai. Orde politik baru telah lahir. Tapi, rupanya perubahan tak selalu menghasilkan kemurnian. Ratusan ribu mahasiswa hari itu bermimpi rakyatlah yang menang. Lalu, pemerintahan baru bisa membawa cita-cita tentang Indonesia yang makmur dan adil, yang bebas represi dari tentara bangsanya sendiri.
Demokratis dan bermartabat. Pokoknya semua hal normatif, dan yang kini terdengar naif. Sepuluh tahun terakhir kita mencatat bahwa Soeharto adalah ”sang tak tersentuh”. Semangat menumbangkan sang diktator satu dekade silam, kini hampir sama kencangnya dengan gairah merayakannya kembali sebagai pahlawan.
Tentang Marcos dan Chun Do Hwan
Apa boleh buat. Mimpi reformasi itu pun kini hanya sepertiganya berhasil. Memang, ada kelegaan bahwa politik kini sudah menjadi urusan sipil. TNI dengan besar hati kembali menjadi militer profesional. Pers boleh bebas bicara, dan partai politik tumbuh seperti jamur. Ekonomi relatif lebih baik, meski banyak yang mengigau bahwa zaman Soeharto keadaan jauh lebih enak. Tak soal. Mungkin mereka adalah orang-orang dari kaum yang memilih perut kenyang, tapi rela jika bermimpi pun dilarang.
Tetapi, sebagai bekas penguasa satu rezim terpanjang dalam sejarah Republik Indonesia—mengalahkan Soekarno, pendahulunya, Soeharto adalah produser sekaligus produk dari satu tradisi politik yang berbahaya bagi demokrasi. Dia percaya rakyat tak butuh demokrasi, karena pemimpin tahu segalanya. Pancasila dipermak menjadi mantra menghidupkan kembali negara organis gaya fasisme Jepang. Soeharto, dengan patrimonialisme yang ditanamkan pada pengikutnya, menjelma menjadi struktur otoriter itu sendiri. Dia tak cukup lagi dilihat sebagai pribadi. Kekuasaan otoriter, oligarki ekonomi bertopang kronisme, tradisi politik “asal bapak senang”, wadah tunggal, penangkapan kaum oposan dengan brutal, agaknya telah menjadi bagian dari ”Soehartoisme”.
Di tengah politik Indonesia yang kian liberal hari ini, ajaran itu mungkin mulai lapuk. Tapi toh, politik liberal itu juga membuat Soeharto bisa menutup hari akhirnya dengan lebih terhormat. Nasibnya, jelas lebih baik ketimbang koleganya bekas presiden Filipina Ferdinand Marcos, yang digulingkan people power pada 1986. Hingga ajalnya tiba, Marcos sempat tak diizinkan pulang ke negerinya oleh penguasa baru hasil reformasi politik di sana. Di Korea Selatan, bekas presiden Chun Do Hwan, yang sebetulnya sulit disebut diktator ulung, tapi tersandung kasus korupsi. Dia akhirnya bersedia masuk bui. Chun lalu dikenang sebagai contoh moral politik bertanggung jawab dari bangsa Korea.
Perginya Soeharto jelas meninggalkan warisan perkara publik yang belum tuntas. Bahkan, kita merasakan Soehartoisme seperti berdenyut kembali. Ketika dia sedang sakit berat pun, tiba-tiba segelintir elite politik melantunkan koor maaf, minta kejahatan politik dan ekonomi Suharto dihapuskan saja dari benak rakyat. Kita lalu seperti putus asa dengan hukum. Lebih parah lagi, kita lupa bahwa penyelesaian kasus Soeharto adalah amanat reformasi, dan telah menjadi satu ketetapan di MPR RI.
Memburu Pewarisnya
Tentu, setelah Soeharto pergi, warisan perkara itu menjadi beban negara, keluarganya dan juga masyarakat. Bagi negara, pintu rekonsiliasi bagi masa lalu lenyap sudah, padahal masih banyak perkara korban pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Orde Baru belum lagi tuntas.
Sepatutnya, saat Soeharto minta maaf dulu, sewaktu dia turun, penguasa baru membawanya ke pengadilan. Mereka yang menjadi korban politik kejahatan atas kemanusiaan, dari tragedi 1965 sampai kasus Lampung, Aceh, Papua, dan banyak lagi, bisa menemukan jawaban pasti secara legal dari negara. Kini, pemerintah tentu menjadi lebih sulit merebut kembali harta yang diselewengkan Soeharto melalui berbagai yayasan, atau mengeduk kembali timbunan uangnya di luar negeri, termasuk mengadili perannya dalam kasus BLBI yang macet itu.
Saya turut bersedih, bukan mengikuti anjuran berkabung nasional selama sepekan itu. Yang menyedihkan adalah kepergian Soeharto dengan warisan perkara. Sebagai bangsa, kita seakan telah gagal memberi contoh yang baik bagaimana menamatkan sebuah transisi dari rezim otoroiter ke demokrasi. Tidak jelasnya status hukum Soeharto sampai dia meninggal, adalah tragedi besar bagi reformasi politik dan hukum Indonesia. Ketidakjelasan kasusnya sekaligus menjadi pendidikan politik buruk bagi generasi penerus, seakan menjadi pemimpin berarti berhak menjadi yang ”tak tersentuh”.
Apa boleh buat. Soeharto adalah diktator yang berhasil. Dia mungkin pergi dengan tenang. Tetapi rakyat yang mencatat kesalahannya, mungkin akan terus memburu keadilan dari siapa pun yang menjadi pewarisnya.
Penulis adalah mantan Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).
Di Balik Awan
Menurutmu salah apa kalo aku tahu-tahu suka dengerin Peter Pan? Ada yang orisinil dengan lagu mereka yang judulnya “Di Balik Awan”.
Sebentar Nana, aku tidak mengajak ngobrol soal orisinalitas. Kamu sudah cukup menguliahi aku soal orisinalitas, tidak ada yang orisinil sekarang, sejak dulu orang orang Romawi sudah bilang nihil nova sub sole, tidak ada yang baru di bawah matahari. Tapi kalau di bawah matahari yang kamu maksud itu (ini aku simpulkan dari omonganmu sendiri, lho) adalah relasi antar manusia di bawah berbagai “matahari” (hukum yang berlaku, hukum apa pun itu), maka bagaimana kalau “di balik awan”, seperti katanya Ariel? Maksudku bagaimana kalau ada sesuatu yang tercipta dari relasi yang terjadi di dalam dirinya sendiri.
Kamu sendiri yang pernah bilang kalau ada ahli genetika dari Johns Hopkins University yang setiap hari kerjaannya cuma ngurusin kromosom dan gen bilang bahwa tidak ada satu pun manusia di dunia yang benar-benar mirip.
Mungkin saat Ariel, atau siapa pun yang nulis lirik Di Balik Awan, dia benar-benar menulis dari dirinya atau membicarakan kebenaran tentang dirinya dan tanpa harapan apapun selain hendak berbagi dengan dunia, bahwa “semua yang kuinginkan, menjauh dari kehidupan…” Perkara baris lanjutannya adalah penyebab radang telinga atau berbagai jenis gangguan THT lainnya aku juga setuju. Industri yang bikin seperti itu, atau dalam proses selanjutnya si penulis gagal menyuarakan kebenaran dari dalam dirinya, atau mencoba memadukannya dengan kebenaran industri; uang broer! duit, fulus, taim is mani, time is money; matane suwek, taim is taim, time is time, waktu ya waktu; uang itu urusanmu sama semua cicilan barang-barangmu.
Hah, lega. Makanya jangan suka hapus MP3 orang sembarangan. Toh, cuma ada dua lagunya Peter Pan di komputerku.
Maaf ya, Nana. Kamu sudah gosok gigi? Oh ya, ikat rambutmu ketinggalan di kamarku. Besok kalau mau ambil telepon dulu aja. Aku mungkin masih belum pulang jam segitu. Dan ingat, jangan main hapus MP3.
Kita memang bukan bangsa tempe
Tentu kita tidak akan bisa dengan enteng menjelaskan konteks ungkapan “kita bukan bangsa tempe!” yang lantang diucapkan Soekarno dan masih bergaung hingga kini, seenteng kita menafsirkan ungkapan dan menggunakannya secara serampangan seperti banyak kita temui kini. Tempe kerap dikaitkan sifat kemalasan, dan mungkin dalam hati peminjam ungkapan itu dalam hati atau benaknya mempertentangkan tempe, buah karya leluhur kita, dengan jenis makanan bangsa lain yang mewakili karakter bangsa tersebut. Tapi peminjam kita yang agung tersebut selalu gagal. Semua orang seolah sepakat membenamkan konteks ungkapan dan bahkan ungkapanitu sendiri dalam lautan mitos yang tak terselami.
Tanyalah setiap orang yang dengan sembrono mengucapkan, “kita ini memang bangsa tempe!”. Lalu bangsa apa kita ini? Pilihlah sebuah makanan khas Indonesia yang tepat mewakili karakter bangsa ini. Dalam “bukan bangsa tempe”, yang disajikan kepada pembaca atau pendengar terutama adalah karakter fisik tempe yang kurang menawan dibandingkan tahu dan lembek jika belum diolah lebih lanjut. Jangan-jangan yang dimaksud Soekarno bukan karakter, tapi tempe dalam peta kuliner Indonesia, yang tidak pernah naik pangkat diolah menjadi bentuk lain dan benar-benar diperhatikan keberadaannya. Dari zaman Mataram sampai zaman modern ini bentuk tempe bisa jadi tidak pernah berubah.
Sujiwo Tejo pernah bilang bahwa kita ini bangsa soto. Orang Surabaya yang suka banget makan soto ternyata tidak menghasilkan Soto Surabaya, yang populer malah Soto Madura dan Soto Ambengan. Rasanya beda sekali dengan Soto Tulungagung (yang dalam lidah Surabaya saya sebenarnya lebih tepat disebut Sup Tulungagung), Soto Kadipiro dari Yogya, Soto Kudus, apalagi Coto Makasar.
Seperti itu, Bung, lebih cerdas dan bernas ketimbang sekedar menggunakan makanan kita untuk menggambarkan sifat-sifat buruk. Soto tidak serta merta dikaitkan dengan sifat atau karakter manusia. Sekilas ucapan itu akan langsung tertangkap di kepala kita sebagai “bangsa pemakan dan penggemar soto”. Sayangnya saya belum selesai baca buku tentang Onghokham. Sejarawan yang hobinya makan itu pasti punya ungkapan tersendiri semacam “bangsa tempe”.
Orang Jerman yang suka sekali makan Bratwurst itu rasanya ya nggak pernah kok mengatainya sesama orang Jerman yang malas seperti “Gandum” misalnya. Apalagi sembrono mengumbar ungkapan yang sebenarnya perlu direnungkan lebih jauh.
Belum lama ini kita tertegun bagaimana para petani kedelai menyita perhatian media yang sedang diharu-biru kondisi kesehatan Soeharto. Lalu kita baru sadar bahwa tempe kita ini sekarang diimpor dari Jepang, bahwa pemerintah terlalu all out mengurusi beras dan melupakan tanaman pangan lain termasuk kedelai.
Di Malang orang suka sekali makan Jangan Sambel. Pedas bukan main, Bung! Kapan-kapan kita main ke Malang dan cari sayur yang isinya didominasi tempe dan cabe itu. Dijamin kita sama-sama meringis kepedasan. Daripada kita sama-sama meringis kecut setelah melihat berita soal tempe dan petani kedelai yang sekarang hidupnya morat-marit, yang kemudian disusul iklan sebuah makanan ringan dari Jepang yang terbuat dari kedelai. Keponakan saya suka sekali sama iklan itu. Lucu memang bagi dia, kedelai yang bentuknya biasa kok bisa jadi seperti ninja dan bisa joget-joget. Tapi buat kita? Hehe. Miris mungkin kata yang tepat.