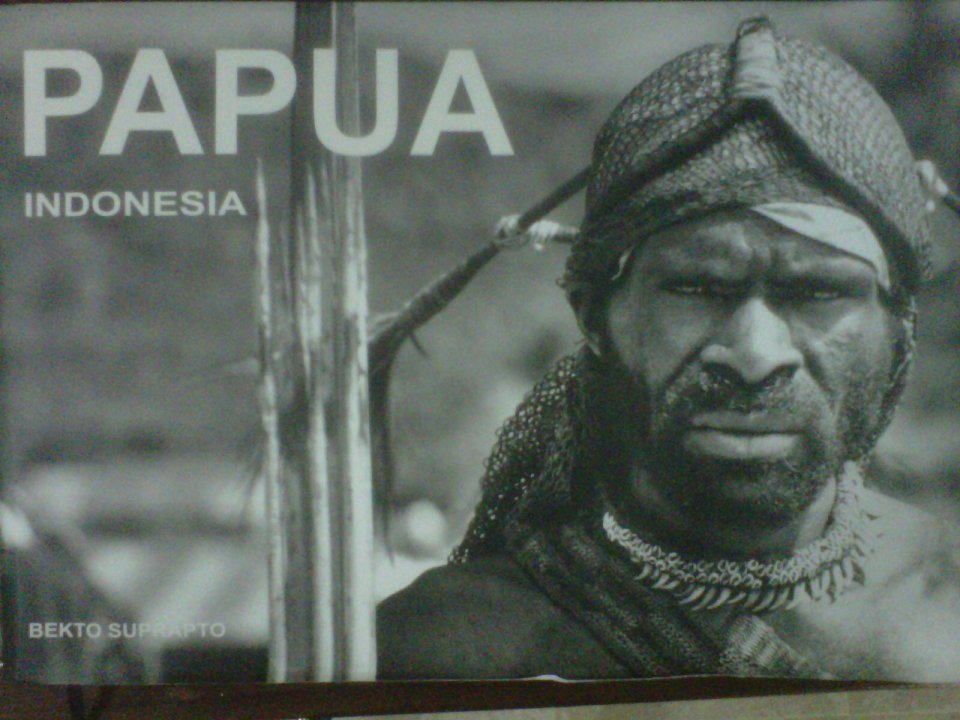(bagian pertama dari entah beberapa tulisan lagi)
Aku berjumpa dengan mahkluk kecil itu pada 19 Agustus 2011 di sebuah jalan yang sibuk di daerah SP IV, kurang lebih 10 kilometer selatan kota Timika. Dia sepertinya hendak menyeberang jalan dan nyaris terlindas mobil yang aku tumpangi.
Pada saat aku turun dan mengambilnya, sebagian dari diriku menginginkan dia, sebagian memintaku untuk menaruhnya di pinggir jalan. Tapi ternyata aku membawanya masuk ke dalam mobil. Semua temanku di dalam mobil pada heran, “ngapain kucing itu dibawa? Kasih tinggal sudah….” Di dalam benakku juga terbayang komentar Sasi, pasti jadinya akan seperti “ih, kucing jelek gitu dibawa pulang” atau “rumah kita ga memungkinkan untuk pelihara kucing”. Lalu menyusul aku teringat akan kesibukan hari ini, masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dan tempat yang harus aku datangi. Tapi entah kenapa aku bergeming.
Aku masukkan dia ke dalam kantong luar tas ranselku. Anehnya, dia tidak berontak seperti yang aku duga. Dia malah sibuk membersihkan dirinya. Dari berat badan dan ukuran tubuhnya, aku menduga saat itu umurnya baru sekitar 6 bulan. Yang membedakan dia dengan kucing-kucing lain yang aku pelihara dan lihat di manapun, di ujung telinga kucing ini ada bulu yang menyembul, memberi kesan bahwa dia bukan kucing ras lokal.
Setibanya di kantor, aku menitipkannya ke seorang teman yang juga suka pelihara kucing. Aku langsung bergegas ke ruang rapat untuk sebuah rapat penting.
Usai rapat, aku mendapatinya sedang duduk diam di atas meja resepsionis kantor. Temanku memberikan sebagian menu makan siangnya untuk kucing itu. Ketika ku tanya makan apa kucing itu, temanku menjawab, “eh, dia makan Kasbi…. suka sekali…mungkin karena lapar, toh…” Aku hanya tersenyum sambil menggendong dia masuk ke tasku lagi. Masih ada pekerjaan lagi yang harus segera aku selesaikan.
Tanpa sadar, sambil memasukkan dia ke dalam kantong tas, aku telah memberinya nama, “Kasbi, ayo masuk… ikut aku kerja dulu ya.”
Setibanya di kantorku, Kasbi yang sudah tertidur terpaksa aku bangunkan karena aku harus mengeluarkan laptop dan barang-barang lain. Setelah itu, aku kembali memasukkan dia ke dalam tas dan memintanya untuk tidur. Nampak jelas bahwa dia masih kebingungan dengan tempat-tempat baru yang dia lihat. Mungkin karena capek dan dipenuhi ketakutan di tengah jalan tadi, dia memilih untuk memulihkan tenaga dan pikirannya dengan melanjutkan tidur.
Kira-kira 2 jam kemudian Kasbi terbangun. Perutnya yang buncit ke samping tidak menghalangi niatnya untuk menjelajah area kantorku. Karena tidak ada yang bisa aku berikan padanya, aku hanya mengawasi dia. Hingga akhirnya aku masukkan dia ke dalam kantong tas ranselku lagi untuk bergegas pulang. Sebelum pulang aku membelikannya sekaleng makanan kucing dewasa di sebuah supermarket di Timika.
Sepanjang perjalanan dari Timika ke Kuala Kencana, Kasbi kembali tertidur dan aku memikirkan begitu banyak hal lain. Satu hal saja yang tidak kupikirkan; urusan sanitasi kucing. Dan benar saja, setibanya di rumah dan disambut gembira Sasi dan setelah dia mulai menjelajah ruang tengah rumahku, Kasbi menentukan tempat boker yang ideal sekali, di sudut dapur persis di bawah rak perabot makan. Kalau ada skala untuk bau yang sangat menyengat, mungkin nilai bau feses Kasbi ini jauh di atas batas kemampuan penciumanku untuk bau yang tidak menyenangkan.
Sambil menciduk pasir di gundukan pasir milik tetangga (yang mestinya akan digunakan untuk membangun rumahnya), aku menyimpulkan bahwa Kasbi harus tidur di luar rumah, kalau dia hilang ya sudah resiko ditanggung si Kasbi. Tapi ternyata Sasi menolak. “Kasian, dia tidur di dalam saja…” Dengan demikian, dimulailah babak baru kehidupan rumah tangga kami….
(bersambung)